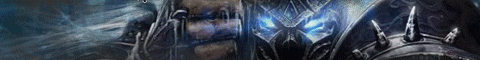A.
Sejarah Perkembangan Ushul
Fiqh
1. Ushul
Fiqh Sebelum Dibukukan
a. Ushul Fiqh Masa
Rasulullah saw.
Ushul fiqh
baru lahir pada abad kedua hijriah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam
semakin luas dan banyak orang yang bukan arab memeluk agama Islam. Karena itu
banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nash, sehingga dirasa
perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nash,
maka lahirlah ilmu ushul fiqh, yang menjadi penuntun dalam memahami nash.[1]
Ushul fiqh
sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan ushul fiqh
sebagai sebuah metode memecahkan hukum. Kalau ada yang bertanya: “Dahulu mana
ushul fiqh dan fiqh?” tentu tidak mudah menjawabnya. Pertanyaan demikian sama
dengan pertanyaan mengenai mana yang lebih dahulu: ayam atau telor.
Musthafa
Said al-Khin memberikan argumentasi bahwa ushul fiqh ada sebelum fiqh.
Alasannya adalah bahwa ushul fiqh merupakan pondasi, sedangkan fiqh merupakan
bangunan yang didirikan di atas pondasi. Karena itulah sudah tentu ushul fiqh
ada mendahului fiqh.[2]
Kesimpulannya, tentu harus ada ushul fiqh sebelum adanya fiqh.
Jawaban
demikian benar apabila ushul fiqh dilihat sebagai metode pengambilan hukum
secara umum, bukan sebuah bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat,
misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat al-Qur’an
atau mencari jawaban dari Rasulullah saw., maka hal itu bisa dipandang sebagai
metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum
harus dicari dari al-Qur’an atau bertanya kepada Rasulullah saw. Akan tetapi,
cara pemecahan demikian belum bisa dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu.
Pemecahan demikian adalah prototipe (bentuk dasar) ushul fiqh, yang
masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk disebut sebagai ilmu ushul fiqh.
Prototipe-prototipe ushul fiqh demikian tentu telah ditemukan
pada masa hidup Rasulullah saw. sendiri. Rasulullah saw. dan para sahabat
berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Ijtihad
tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan
rumit seperti yang dirumuskan para ulama dikemudian hari.
Contoh
ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika dua orang sahabat bepergian,
kemudian tibalah waktu shalat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk wudlu.
Keduanya lalu bertayammum dengan debu yang suci dan melaksanakan shalat.
Kemudian mereka menemukan air pada waktu shalat belum habis. Salah satu
mengulang shalat sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah
saw. dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang tidak mengulang,
Rasulullah bersabda: “Engkau telah memenuhi sunnah dan shalatmu mencukupi.”
Kepada orang yang berwudlu dan mengulang shalatnya, Rasulullah saw. menyatakan:
“Bagimu dua pahala.”
Dalam
kisah di atas, sahabat melakukan ijtihad dalam memecahkan persoalan ketika
menemukan air setelah shalat selesai dikerjakan dengan tayammum. Mereka berbeda
dalam menyikapi persoalan demikian, ada yang mengulang shalat dengan wudlu dan
ada yang tidak. Akhirnya, Rasulullah saw. membenarkan hasil ijtihad dua sahabat
tersebut.
b. Ushul Fiqh Masa
Sahabat
Masa
sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan
Rasulullah saw. kepada masa Rasulullah saw. tidak lagi mendampingi umat Islam.
Ketika Rasulullah saw. masih hidup, sahabat menggunakan tiga sumber penting dalam
pemecahan hukum, yaitu al-Qur’an, sunnah, dan ra’yu (nalar).
Meninggalnya
Rasulullah saw. memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus
baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan
fasilitas khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang
hukum, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah Ibn Mas’ud,
Abdullah Ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian telah
dimulai pada masa Rasulullah saw. sendiri.[3]
Periode
sahabat, dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para
sahabat menggunakan ushul fiqh sebagai alat untuk
berijtihad. Hanya saja, ushul fiqh yang mereka gunakan baru dalam bentuknya
yang paling awal, dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana
yang kita kenal sekarang.[4]
Pada era
sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum, para sahabat
telah mempraktikkan ijma’, qiyas, dan istishlah (maslahah mursalah)
bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulus dalam al-Qur’an
dan as-Sunnah.[5] Pertama,
khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang
persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam
bidang hukum. Keputusan musyawarah tersebut biasanya diikuti oleh para sahabat
yang lain sehingga memunculkan kesepakatan sahabat. Itulah momentum lahirnya
ijma’ sahabat, yang di kemudian hari diakui oleh sebagian ulama, khususnya oleh
Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya sebagai ijma’ yang paling bisa diterima.
Kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal
(ra’yu), yang berupa qiyas dan maslahah. Penggunaan ra’yu (nalar)
untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus
baru yang belum muncul pada masa Rasulullah saw. Qiyas dilakukan dengan
mencarikan kasus-kasus baru contoh pemecahan hukum yang sama dan kemudian
hukumnya disamakan.
Penggunaan
maslahah juga menjadi bagian penting fiqh sahabat. Umar bin Khattab dikenal
sebagai sahabat yang banyak memperkenalkan penggunaan pertimbangan maslahah
dalam pemecahan hukum. Hasil penggunaan pertimbangan maslahah tersebut dapat
dilihat dalam pengumpulan al-Qur’an dalam satu mushaf, pengucapan talak tiga
kali dalam satu majlis dipandang sebagai talak tiga, tidak memberlakukan
hukuman potong tangan di waktu paceklik, penggunaan pajak tanah (kharaj),
pemberhentian jatah zakat bagi muallaf, dan sebagainya.
Sahabat
juga memiliki pandangan berbeda dalam memahami apa yang dimaksud oleh al-Qur’an
dan sunnah. Contoh perbedaan pendapat tersebut antara lain dalam kasus pemahaman
ayat iddah dalam QS. al-Baqarah 228:
وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
“Perempuan-perempuan
yang ditalak hendaknya menunggu selama tiga quru'.”
Kata quru’
dalam ayat di atas memiliki pengertian ganda (polisemi), yaitu suci dan haid.
Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali, Utsman, dan Abu Musa al-Asy’ari mengartikan quru’
dalam ayat di atas dengan pengertian haid, sedangkan Aisyah, Zaid bin Tsabit,
dan Ibn Umar mengartikannya dengan suci.[6]
Itu berarti ada perbedaan mengenai persoalan lafal musytarak (polisemi).
Secara
umum, sebagaimana pada masa Rasulullah saw., ushul fiqh pada era sahabat masih
belum menjadi bahan kajian ilmiah. Sahabat memang sering berbeda pandangan dan
berargumentasi untuk mengkaji persoalan hukum. Akan tetapi, dialog semacam itu
belum mengarah kepada pembentukan sebuah bidang kajian khusus tentang
metodologi. Pertukaran pikiran yang dilakukan sahabat lebih bersifat praktis
untuk menjawab permasalahan. Pembahasan hukum yang dilakukan sahabat masih
terbatas kepada pemberian fatwa atas pertanyaan atau permasalahan yang muncul,
belum sampai kepada perluasan kajian hukum Islam kepada masalah metodologi.[7]
c. Ushul Fiqh Masa Tabi’in
Tabi’in adalah generasi setelah sahabat. Mereka
bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi’in,
metode istinbath menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah
luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak
para tabi’in hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk
berfatwa dan berijtihad, antara lain Sa’id ibn al-Musayyab di Madinah dan
Alqamah ibn al-Qays serta Ibrahim al-Nakha’i di Irak.[8]
Metode istinbath
tabi’in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbath sahabat.
Hanya saja pada masa tabi’in ini mulai muncul dua fenomena penting:
1) Pemalsuan hadits
2) Perdebatan mengenai
penggunaan ra’yu yang memunculkan kelompok Irak (ahl al-ra’yi)
dan kelompok Madinah (ahl al-hadits).
Dengan
demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas disertai
dengan perbedaan kelompok ahli hukum (fuqaha) berdasarkan wilayah
geografis.
Dalam
melakukan ijtihad, sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi’in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang
dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi, dalam pada itu, selain merujuk
Al-Qur’an dan sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru,
yaitu ijma’ ash-shahabi, ijma’ahl al madinah, fatwa ash shahabi, qiyas, dan
maslahah mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi sahabat.[9]
Masa
tabi’in banyak yang melakukan istinbath dengan berbagai sudut pandang dan
akhirnya juga mempengarhi konsekuensi hukum dari suatu masalah. Contohnya;
ulama fiqh Irak lebih dikenal dengan penggunaan ar ra’yu, dalam
setiap kasus yang dihadapi mereka mencari illatnya, sehingga dengan illat
ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan kasus yang sudah
ada nashnya. Adapun para ulama Madinah banyak menggunakan hadits-hadits
Rasulullah SAW, karena mereka dengan mudah melacak sunnah Rasulullah di daerah
tersebut. Disinilah awal perbedaan dalam mengistinbathkan hukum
dikalangan ulama fiqh. Akibatnya, muncul tiga kelompok ulama’, yaitu Madrasah
al-Iraq, Madrasah Al-Kufah, Madrasah Al- Madinah.[10]
Pada perkembangan selanjutnya madrasah al-iraq dan madrasah al-kufah dikenal
dengan sebutan madrasah al-ra’yi, sedangkan madrasah al-Madinah dikenal
dengan sebutan madrasah al- hadits.
d. Ushul Fiqh Masa Imam-imam
Mujtahid Sebelum Imam Syafi’i
Imam Abu
Hanifah an-Nu’man, pendiri madzhab Hanafi menjelaskan dasar-dasar istinbath-nya
yaitu, berpegang kepada Kitabullah, jika tidak ditemukan di dalamnya, ia
berpegang pada Sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di dalamnya ia berpegang
kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, ia
akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan tidak akan mengeluarkan
fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah
terkenal banyak melakukan qiyas dan istihsan.
Demikian
pula Imam Malik bin Anas, pendiri madzhab Maliki, dalam berijtihad mempunyai
metode yang cukup jelas, seperti tergambar dalam sikapnya dalam mempertahankan
praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum.[11]
Imam Malik
dan orang-orang Madinah sangat menghargai amal orang-orang Madinah. Ketika ada
hadits Rasulullah saw. diriwayatkan secara ahad (diriwayatkan oleh satu
atau beberapa orang tapi tidak mencapai derajat pasti/mutawatir) bertentangan
dengan amal ahli Madinah, amal ahli Madinah lah yang dipergunakan. Alasannya
adalah bahwa amalan orang Madinah adalah peninggalan para sahabat yang hidup di
Madinah dan mendapatkan petunjuk dari Rasulullah saw. Amalan orang Madinah
telah dilakukan oleh banyak sekali sahabat yang tidak mungkin menyalahi ajaran
Rasulullah saw., yang selama sepuluh tahun hidup di Madinah.
Oleh
karena itu, Imam Malik pernah berkirim surat kepada Imam al-Laits, imam orang
Mesir, yang isinya mengajak Imam Laits untuk mempergunakan amalan orang
Madinah. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Imam Laits karena ia lebih
setuju mengutamakan hadits, meskipun hadits itu ahad.
Orang
Irak, khususnya Imam Abu Hanifah mempergunakan istihsan apabila hasil qiyas,
meskipun benar secara metode, dirasa tidak sesuai dengan nilai dasar hukum
Islam. Penggunaan istihsan oleh Imam Abu Hanifah tersebut ditentang
ulama lain dan dipandang sebagai pemecahan hukum berdasarkan hawa nafsu. Orang-orang
Irak juga dikritik karena mempergunakan ra’yu secara berlebihan. Sementara
itu, bagi orang Irak mempergunakan petunjuk umum ayat dan ra’yu lebih
dirasa memadai dibandingkan mempergunakan riwayat dari Rasulullah saw., tetapi
riwayat tersebut tidak meyakinkan kesahihannya.
2. Pembukuan
Ushul Fiqh
Pada
penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i
(150 H-204 H) tampil berperan dalam meramu, mensistematisasi, dan membukukan
Ushul Fiqh. Imam Syafi’i banyak mengetahui tentang metodologi istinbath
para imam mujtahid sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan metode
istinbath para sahabat, serta mengetahui di mana kelemahan dan
keunggulannya.
Imam
Syafi’i menyusun sebuah buku yang diberinya judul al-Kitab dan kemudian
dikenal dengan sebutan al-Risalah yang berarti sepucuk surat. Dikenal
demikian karena buku itu pada mulanya merupakan lembaran-lembaran surat yang
dikirimkan kepada Abdurrahman al-Mahdi (w. 198 H), seorang pembesar dan ahli
hadits ketika itu. Munculnya buku al-Risalah merupakan fase awal dari
perkembangan ushul fiqh sebagai satu disiplin ilmu.
Kandungan
kitab al-risalah ini pada masa sesudah Imam Syafi’i menjadi bahan
pembahasan para ulama ushul fiqh secara luas. Pembahasan mereka ada yang
berbentuk mensyarh (menjelaskan) secara luas apa yang dikemukakan oleh
imam Syafi’i dalam kitabnya itu, tanpa mengubah atau mengurangi dari isi
kitabnya itu. Juga ada yang melakukan pembahasan bersifat analisis terhadap
pendapat dan teori Imam Syafi’i, dengan mengemukakan aspek-aspek kekuatan dan
kelemahan teori imam Syafi’i dan terkadang mengemukakan pendapat yang
bertentangan dengan imam Syafi’i. Misalnya, ulama Ushul fiqh dari kalangan
Hanafi yang mengakui teori-teori Imam Syafi’i akan tetapi mereka menambahkan
metode atau teori lainnya yaitu istihsan dan ‘urf dalam mengistinbathkan
hukum. Disamping itu, ulama ushul fiqh malikiyyah juga melakukan hal
yang sama, yaitu; Ijma’ Ahlul Madinah (kesepakatan penduduk madinah).[12]
B. Aliran-aliran
dalam Ushul Fiqh
Sejarah
perkembangan ushul fiqh menunjukkan bahwa ilmu tersebut tidak berhenti,
melainkan berkembang secara dinamis. Ada beberapa aliran metode penulisan ushul
fiqh yang saat ini dikenal. Secara umum, para ahli membagi aliran penulisan
ushul fiqh menjadi dua, yaitu mutakallimin (Syafi’iyyah) dan aliran fuqaha
(Aliran Hanafiyah). Dari kedua aliran tersebut lahir aliran gabungan. Tiga
aliran utama tersebut diuraikan sebagai berikut:
1.
Aliran Mutakallimin
Aliran mutakallimin
disebut juga dengan aliran Syafi’iyyah. Alasan penamaan tersebut bisa dipahami
mengingat karya-karya ushul fiqh aliran mutakallimin banyak lahir dari
kalangan Syafi’iyyah. Aliran ini membangun ushul fiqih secara teoritis murni
tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula dalam
menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil
naqli, tanpa dipengaruhi masalah furu’ dan madzhab, sehingga adakalanya
kaidah tersebut sesuai dengan masalah furu’ dan adakalanya tidak sesuai.
Selain itu, setiap permasalahan yang didukung naqli dapat dijadikan kaidah.
Dalam aliran
ini, mereka mempelajari ilmu ushul fiqih sebagai suatu disiplin ilmu yang terlepas
dari pengaruh madzhab atau furu’, faktornya karena[13]:
a. Imam Syafi’i sendiri
yang menetapkan bahwa dasar-dasar tasyri’ itu memang terlepas dari
pengaruh furu’.
b. Mereka berkeinginan
untuk mewujudkan pembentukan kaidah-kaidah atas dasar-dasar yang kuat, tanpa
terikat dengan furu’ atau madzhab.
c. Mereka membuat
penguat kaidah-kaidah yang telah dibuatnya dengan menggunakan berbagai macam
dalil, tanpa menghiraukan apakah kaidah tersebut memperkuat madzhab atau
melemahkannya.
Aliran
Mutakakallimin lebih berorienntasi kepada hal-hal berikut, yakni;[14]
a. Analisis kasus-kasus
b. Formulasi
kaidah-kaidah hukum (al-qawa’id)
c. Aplikasi qiyas yang
disertai penalaran rasio sejauh mungkin
d. Mengkonstruksi
isu-isu fundamental teori hukum tanpa terikat dengan fakta hukum yang kasuistis
dan pikiran hukum madzhab fiqh yang ada.
Semua
pemikiran mereka, dapat dilihat dari hasil karya mereka, dalam bentuk tiga
kitab, yang kemudian dikenal dengan sebutan al-Arkan al-Tsalatsah yaitu
sebagai berikut:
a. Kitab al-Mu’tamad,
karya Abu Husain Muhammad ibn ‘Ali al-Bashriy (w. 412 H).
b.
Kitab al-Burhan, karya al-Imam al-Haramain (w. 474 H).
c.
Kitab al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, karya al-Ghazali (w. 500 H).
d.
Al Mahsul
karya fakhr al-Din Muhammad bin Umar al- Razi al-Syafi’i (w. 606 H). Kitab ini
diringkas oleh dua orang dengan judul;
1)
Al-Hasil oleh
Taj al-Din Muhammad bin Hasan al-Armawi (w. 656 H).
2.
Aliran Fuqaha
Aliran yang
kedua ini dikenal dengan aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama
madzhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha karena dalam sistem penulisannya
banyak diwarnai oleh contoh-contoh fiqh. Dalam merumuskan kaidah ushul fiqh,
mereka berpedoman pada pendapat-pendapat fiqh Abu Hanifah dan pendapat-pendapat
para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh.[16]
Di antara
kitab-kitab standar dalam aliran fuqaha ini antara lain: kitab al-Ushul
(Imam Abu Hasan al-Karakhiy), kitab al-Ushul (Abu Bakar al-Jashash), Ushul
al-Syarakhsi (Imam al-Syarakhsi), Ta’shish an-Nadzar (Imam Abu Zaid
al-Dabusi), dan al-Kasyaf al-Asrar (Imam al-Bazdawi).
3.
Aliran Gabungan
Pada
perkembangannya muncul tren untuk menggabungkan kitab ushul fiqh aliran mutakallimin
dan Hanafiyah. Metode penulisan ushul fiqh aliran gabungan adalah dengan
membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fiqh. Persoalan hukum
yang dibahas imam-imam madzhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi
sandarannya.
Karya-karya
gabungan lahir dari kalangan Hanafi dan kemudian diikuti kalangan Syafi’iyyah.
Dari kalangan Hanafi lahir kitab Badi’ al-Nidzam al-Jami‘ bayn Kitabay
al-Bazdawi wa al-Ihkam yang merupakan gabungan antara kitab Ushul
karya al-Bazdawi dan al-Ihkam karya al-Amidi. Kitab tersebut ditulis
oleh Mudzaffar al-Din Ahmad bin Ali al-Hanafi. Ada pula kitab Tanqih Ushul
karya Shadr al-Syariah al-Hanafi. Kitab tersebut adalah ringkasan dari Kitab al-Mahshul
karya Imam al-Razi, Muntaha al-Wushul (al-Sul) karya Imam
Ibnu Hajib, dan Ushul al-Bazdawi. Kitab tersebut ia syarah sendiri
dengan judul karya Shadr al-Syari’ah al-Hanafi. Kemudian lahir kitab Syarh
al-Tawdlih karya Sa’d al-Din al-Taftazani al-Syafii dan Jami’ al-Jawami’
karya Taj al-Din al-Subki al-Syafi’i.
Tiga aliran
di atas adalah aliran utama dalam ushul fiqh. Sebenarnya ada pula yang
memasukkan Takhrij al-Furu’ ‘ala al-Ushul dan aliran khusus sebagai
aliran lain dalam ushul fiqh. Aliran Takhrij al-Furu’ ‘ala al-Ushul dipandang
berwujud berdasarkan dua kitab yang secara jelas menyebut istilah tersebut,
yaitu Kitab Takhrij al-Furu’ ‘ala al-Ushul karya al-Isnawi al-Syafi‘i dan
Takhrij al-Furu’ ‘ala al-Ushul karya al-Zanjani al-Hanafi. Sementara
itu, aliran khusus adalah aliran yang mengkaji satu pokok bahasan ushul fiqh
tertentu secara panjang lebar, seperti mengenai maslahah mursalah
sebagaimana dilakukan oleh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat atau oleh
Muhammad Thahir ‘Asyur dalam Maqashid al-Syariah.
KESIMPULAN
Ilmu ushul fiqh dilihat dari sejarah dan perkembangannya,
maka dapat dibagi secara umum menjadi dua; yakni ushul fiqh sebelum pembukuan
dan pembukuan ushul fiqh. Ushul fiqh sebelum pembukuan dimulai dari masa
Rasulullah SAW dilanjutkan generasi Sahabat, generasi Tabi’in, generasi imam
mujtahid sebelum Imam Syafi’i.
Pada Masa Rasululah SAW sendiri ushul fiqh sudah terbukti
dengan peristiwa yang dialami oleh dua sahabat sedang bepergian lalu tiba waktu
shalat, lalu mereka hendak mengerjakan shalat akan tetapi tidak ada air. Keduanya lalu bertayammum dengan debu yang
suci dan melaksanakan shalat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu shalat
belum habis. Salah satu mengulang shalat sedangkan yang lain tidak. Keduanya
lalu mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang
tidak mengulang, Rasulullah bersabda: “Engkau telah memenuhi sunnah dan
shalatmu mencukupi.” Kepada orang yang berwudlu dan mengulang shalatnya,
Rasulullah saw. menyatakan: “Bagimu dua pahala.”
Pada era sahabat masih belum menjadi bahan kajian ilmiah. Sahabat memang
sering berbeda pandangan dan berargumentasi untuk mengkaji persoalan hukum.
Akan tetapi, dialog semacam itu belum mengarah kepada pembentukan sebuah bidang
kajian khusus tentang metodologi. Pertukaran pikiran yang dilakukan sahabat
lebih bersifat praktis untuk menjawab permasalahan. Pembahasan hukum yang
dilakukan sahabat masih terbatas kepada pemberian fatwa atas pertanyaan atau
permasalahan yang muncul, belum sampai kepada perluasan kajian hukum Islam
kepada masalah metodologi.
Dalam melakukan ijtihad, sebagaimana
generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi’in juga menempuh
langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka.
Akan tetapi, dalam pada itu, selain merujuk Al-Qur’an dan sunnah, mereka telah
memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma’ ash-shahabi, ijma’ahl
al madinah, fatwa ash shahabi, qiyas, dan maslahah mursalah yang
telah dihasilkan oleh generasi sahabat.
Selanjutnya, pada masa Imam Mujtahid
sebelum Imam Syaf’i adalah seperti pada masa Imam Malik dengan
alirannya (malikiyyah), dan Imam Hanafi dengan alirannya (hanafiyyah). Imam
maliki mempunyai metode ijtihad yang cukup jelas, seperti mempertahankan
praktih penduduk madinah sebagai sumber hukum. Sedangkan imam hanafi
menjelaskan dasar-dasar istinbatnya yakni; berpegang kepada Kitabullah, jika tidak ditemukan
di dalamnya, ia berpegang pada Sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di
dalamnya ia berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka
berbeda pendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan
tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dalam melakukan ijtihad,
Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan istihsan.
Selanjutnya masa pembukuan ushul fiqh
yakni pada penghujung abad
kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i (150 H-204 H)
tampil berperan dalam meramu, mensistematisasi, dan membukukan Ushul Fiqh. Imam
Syafi’i banyak mengetahui tentang metodologi istinbath para imam
mujtahid sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan metode istinbath
para sahabat, serta mengetahui di mana kelemahan dan keunggulannya.
Aliran dalam ushul fiqh terbagi menjadi
tiga, yakni; aliran mutakallimin (Syafi’iyyah), aliran fuqaha’
(hanafiyyah), dan aliran gabungan.
Aliran Mutakallimin; aliran ini membangun ushul fiqih secara teoritis
murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula
dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari
dalil naqli, tanpa dipengaruhi masalah furu’ dan madzhab, sehingga
adakalanya kaidah tersebut sesuai dengan masalah furu’ dan adakalanya
tidak sesuai. Selain itu, setiap permasalahan yang didukung naqli dapat
dijadikan kaidah.
Aliran yang kedua ini dikenal dengan
aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama madzhab Hanafi. Dinamakan aliran
fuqaha karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh
contoh-contoh fiqh. Dalam merumuskan kaidah ushul fiqh, mereka berpedoman pada
pendapat-pendapat fiqh Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya serta
melengkapinya dengan contoh-contoh.
Pada perkembangannya muncul tren untuk
menggabungkan kitab ushul fiqh aliran mutakallimin dan Hanafiyah. Metode
penulisan ushul fiqh aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam
realitas persoalan-persoalan fiqh. Persoalan hukum yang dibahas imam-imam
madzhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya dan itu dikatakan sebagai aliran
gabungan.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Khudlary, Muhammad, Tarikh Tasyri’ al-Islamy,
Surabaya: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.
Alwani, Thaha Jabir, Source Methodology in Islamic
Jurisprudence, Virginia: IIIT, 1994.
Anhari,
Masykur, Ushul Fiqh, Surabaya:
Diantama, 2008.
Asmawi, Perbandingan
Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011.
Dahlan, Abd. Rahman,
Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011.
Effendi, Satria
dan M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005.
Haroen, Nasrun,
Ushul Fiqh, Jakarta: Logos, 1996.
Karim, A.
Syafi’i, Fiqh Ushul Fiqh,
Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Ma’ruf Al-Dawalibi, Muhammad, Al-Madkhal ila ilm al-ushul al-Fiqh, Damaskus:
Universitas Damaskus, Cet. II, 1959.
Ma’shum Zein, Muhammad , Ilmu Ushul Fiqh, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
Sa‘id al-Khin, Muhammad, Atsar al-Ikhtilaf fi
al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtialaf al-Fuqaha, Beirut: Muassassah
al-Risalah, 1994.
[1] A. Syafi’i Karim, Fiqh Ushul
Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 45-46.
[2] Muhammad Sa‘id al-Khinn, Atsar
al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtialaf al-Fuqaha (Beirut:
Muassassah al-Risalah, 1994) 122-123.
[3] Thaha Jabir Alwani, Source Methodology
in Islamic Jurisprudence (Virginia: IIIT, 1994), 19.
[4] Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta:
Amzah, 2011), hal. 21.
[5] Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh
(Jakarta: Prenada Media, 2005), 17.
[6] Musthafa Sa‘id al-Khinn. Atsar, 72.
[7] Muhammad al-Khudlary, Tarikh Tasyri’
al-Islamy (Surabaya: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt), 114.
[8] Satria Effendi dan M. Zein, Ushul
Fiqh, 17-18.
[9] Abd. Rahman Dahlan, Op.Cit, 23.
[10] Muhammad Ma’ruf Al-Dawalibi, Al-Madkhal
ila ilm al-ushul al-Fiqh (Damaskus: Universitas Damaskus, Cet. II, 1959),
hal. 93.
[11] Satria
Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, 18.
[12] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta:
Logos, 1996), hal. 10
[13]
Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah, 2008),
39.
[14] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta:
Amzah, 2011), 8.
[15] Masykur Anhari, Ushul Fiqh (Surabaya:
Diantama, 2008), hal. 10
[16] Satria
Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, 25.
[17] Rachmat
Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih , Cet IV (Bandung: Pustaka Setia,
2010), hal. 187.